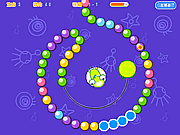- Back to Home »
- Peradaban Islam »
- Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq
Posted by : LaSaro'
Senin, 14 Januari 2013
KHALIFAH ABU BAKAR
A.
Biografi Abu Bakar
Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Abi Quhafah
al-Taimiy. Sebelum masuk Islam ia bernama ‘Abd. Al-Ka’bah, kemudian setelah ia
memeluk Islam nama tersebut diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah yang Akrab
dipanggil dengan Abu Bakar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa gelar tersebut
melekat sebagai nama penggilan karena beliau termasuk orang yang mula-mula
memeluk Islam.[1]
Sedangkan gelar ash-shiddiq merupakan julukan yang diberikan
kepadanya karena ia termasuk orang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi’raj Nabi pada saat sejumlah masyarakat Arab tidak mempercayainya karena mengukur peristiwa tersebut dengan logika murni.[2]
kepadanya karena ia termasuk orang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi’raj Nabi pada saat sejumlah masyarakat Arab tidak mempercayainya karena mengukur peristiwa tersebut dengan logika murni.[2]
Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 M. (dua tahun setelah
kelahiran Rasulullah).[3] Ia termasuk golongan orang
yang memeluk Islam tanpa banyak pertimbangan. Sebelum memeluk Islam, ia
merupakan seorang saudagar kaya yang mempunyai pengaruh yang cukup besar
dikalangan bangsa Arab. Namun setelah ia memeluk Islam, perhatiannya sepenuhnya
dicurahkan kepada Islam sehingga aktivitas perdagangan yang dilakukannya hanya
sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari.[4]
Selain daripada itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur dan dermawan serta senang beramal untuk kepentingan perjuangan Islam. Bukti kedermawanan tersebut sebagaimana dilukiskan dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah SAW. Mempersiapkan pasukan menuju Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan semua harta yang dimilikinya dan tidak ada lagi yang tersisa.[5]
Selain daripada itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur dan dermawan serta senang beramal untuk kepentingan perjuangan Islam. Bukti kedermawanan tersebut sebagaimana dilukiskan dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah SAW. Mempersiapkan pasukan menuju Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan semua harta yang dimilikinya dan tidak ada lagi yang tersisa.[5]
Ketika terjadi peristiwa hijrah, Abu Bakar merupakan
sahabat yang setia mengawal perjalanan Nabi hingga tiba di Madinah. Penderitaan
yang dialaminya dalam peristiwa tersebut serta ancaman maut yang mengintainya
setiap saat tidak pernah menyurutkan semangat kesetiaannya terhadap Nabi SAW.
Dan agama yang dibawanya. Demikian pula, Abu Bakar senantiasa ikut bertempur
dalam hampir semua peperangan bersama Rasulullah.[6]
B.
Proses Pembentukan Khilafah
Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan bahwa setiap makhluk
yang bernyawa pasti mengalami kematian, tak terkecuali
kekasih-Nya sendiri yang bernama Muhammad SAW (QS 3: 144). Namun kematiannya
ternyata disikapi dengan emosional oleh sahabat-sahabatnya yang tidak percaya
akan kematian Nabinya, seakan mereka lupa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah
manusia seperti mereka pula. Abu Bakar dengan imannya yang hampir mendekati
sempurna tampil sebagai pemecah kekalutan sekaligus menebarkan ketentraman kaum
muslimin saat itu dengan membacakan firman Allah SWT QS Al-Imran (3): 144
sebagai berikut:
$tBur JptèC žwÎ) ×Aqß™u‘ ô‰s% ôMn=yz `ÏB Ï&Î#ö7s% ã@ß™”9$# 4 û'ïÎ*sùr& |N$¨B ÷rr& Ÿ@ÏFè% ÷Läêö6n=s)R$##’n?tã öNä3Î6»s)ôãr& 4 `tBur ó=Î=s)Ztƒ 4’n?tã Ïmø‹t6É)tã `n=sù §ŽÛØtƒ ©!$# $\«ø‹x© 3 “Ì“ôfu‹y™ur ª!$# tûïÌÅ6»¤±9$# ÇÊÍÍÈ
Terjemahannya:
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah
berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh
kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka
ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan
memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.[7]
Ayat itu merupakan bentuk penyadaran yang dilakukan Abu
Bakar untuk menghilangkan keragu-raguan atas wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar
nampaknya sangat memahami kondisi spritual kaum muslimin saat itu terutama para
sahabat. Sehingga pendekatan retorika yang digunakan adalah pendekatan nash
Al-Qur’an, apalagi pendekatan ditopang oleh pengetahuan para sahabat tentang
Al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam.
Setelah Abu Bakar melantunkan ayat tersebut, Umar Ibn
Khattab puntersungkur dan menyadari kekeliruannya ternyata Muhammad saw adalah
sama dengan Nabi-nabi sebelumnya yang mempunyai hak kematiannya. Demikian juga
dengan para sahabat yang lain seperti Ibn Abbas yang tersentak kesadarannya
jika ayat itu pernah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.[8]
Kesadaran para sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW
tidak menyebabkan mereka terlalu larut dalam kedukaan. Mereka pun menyadari
bahwa saat ini tidak ada lagi wahyu yang akan turun dan tidak ada lagi hadist
yang terbit dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang
tersisa hanyalah iman dan menjadi harta diri yang tak ternilai harganya, bahkan
kelak menjadi pemicu dan pemacu keberhasilan perjuangan kaum muslimin dalam
mengembangkan syiar agamanya.
Naluri ketergantungan pada sesuatu yang superioritas atas
dirinya mendorong kaum Anshar untuk mengambil prakarsa pembentukan
khilafah dengan menetapkan salah seorang dari mereka sebagai khalifah atau pengganti
peran Nabi SAW. Dalam mengatur Madinah dan upaya pengembangan syiar Islam.[9]
Sungguh menarik prakarsa pembentukan khilafah justru atas
inisiatif kaum Anshar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj merupakan penduduk
asli Madinah.[10]
Kondisi demikian disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, kaum Anshar adalah penduduk asli Madinah yang banyak
menolong Nabi SAW. Dan kaum muslimin dari Mekkah. Sedangkan faktor kedua adalah sense of crisis
(kepekaan terhadap Krisis) yang dimiliki kaum Anshar dalam menyikapi kevakuman
kepemimpinan. Kaum Anshar nampaknya menyadari sepenuhnya bahaya dari sebuah
kevakuman yaitu hilangnnya kontrol atau kendali atas pengaruh syiar Islam pada
diri kaum muslimin yang terbesar didalam berbagai suku di kota Mekkah, Madinah
dan sebagian kecilnya Jazirah Arab.
Ketika kaum Muhajirin dan Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah
terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan
argumentasinya tentang siapa yang layak
sebagai khalifah.
Selanjutnya Abu Bakar menawarkan pola dualisme
kepemimpinan sekedar mewujudkan keadilan di antara keduanya dan demi menjaga
persatuan umat Islam. Semula pendapat ini diterima oleh kaum Anshar, namun Umar
bin Khattab tidak menyetujui adanya dualisme kepemimpinan di kalangan suku
Arab, karena Nabinya bukan berasal dari kaum Anshar. Pendapat Umar bin Khattab
mendapat perlawanan keras dari al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamur (kaum
Anshar), dan sempat terjadi perkelahian kecil diantara keduanya.[11] Di tengah perdebatan
tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon yaitu Abu Ubaidah bin Jahrah dan Umar
bin Khattab. Pengajuan dua calon ternyata menimbulkan kegaduhan dan
perselisihan karena diantara keduanya terdapat perbedaan kualitas, terutama
menyangkut wibawa dan kedudukan.
Tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan perselisihan itu
terus terjadi, maka dengan suaranya yang lantang beliau membaiat Abu Bakar
sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaitan terus
berlanjut seperti yang dilakukan oleh Basyir bin Sa’ad beserta pengikutnya dan
kaum muslimin dari suku Aus.[12]
Proses pembaitan Abu Bakar sebagai khalifah ternyata
tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar
seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin al-Abbas, Zubair
bin al-Awwam bin al-As, Khalid bin Sa’id, Miqdad bin Amir, Salman al-farisi,
Abu Zar al-Gifari, Ammar bin Yasir, Bara’bin Azib dan Ubai bin Ka’ab. Telah
terjadi pertemuan sebagian kecil kaum Anshar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah
Fatimah mereka bermaksud membaiat Ali, dengan anggapan Ali lebih patut menjadi
khalifah karena Ali berasal dari Bani Hasyim yang berarti Ahlulbait
Rasulullah saw.[13]
Keengganan Ali bin Abi Thalib serta kemungkinan adanya
segelintir kaum Muhajirin dari Bani Hasyim ditepis sebagian ahli sejarah dengan
kesaksian Sa’ad bin Zaid tentang tidak adanya orang yang tertinggal dalam
proses pembaitan Abu Bakar sebagai khalifah.[14]
Setelah Abu
Bakat terpilih menjadi khalifah, Abu Bakar kemudian menyampaikan pidato yang
memuat pernyataan antara, bahwa :
1.
Dia mengakui[15]
bahwa dirinya bukanlah orang terbaik.
2.
Dia harus dibantu hanya selama dirinya berbuat
baik dan harus diluruskan bila dia
berbuat tidak baik (in asa'tu).
3.
Dia akan memberikan hak setiap orang tanpa
membedakan yang kuat dengan yang lemah.
4. Ketaatan
kepadanya tergantung pada ketaatannya kepada Allah.
Dijumpai fenomena menarik dari proses pembaitan Abu
Bakar, bahwa isu menjaga persatuan dan menghindarkan perpecahan di kalangan
umat Islam saat itu menjadi argumentasi Abu Bakar untuk meyakinkan
kekhalifahannya. Argumentasi ini cukup efektif karena kondisi sosial umat Islam
saat itu di ambang krisis persatuan. Hal itu ditandai dengan munculnya
orang-orang murtad, keengganan sejumlah suku membayar zakat dan pajak.
C. Kekhalifahan Abu Bakar
Masa kakhalifahan Abu Bakar merupakan masa kritis
perjalanan syiar Islam karena dihadapkan sejumlah masalah seperti ridat
atau kemurtadan dan ketidaksetiaan. Beberapa anggota suku muslim menolak untuk
membayar zakat kepada khalifah untuk Baitul Mal (perbendaharaan publik).
Kemudian masalah berikutnya adalah munculnya beberapa kafir yang menyatakan
dirinya sebagai Nabi, serta sejumlah pemberontakan-pemberontakan kecil yang
merupakan bibit-bibit perpecahan.[16]
Semasa hidupnya, Rasulullah saw pernah mengirimkan satu
ekspedisi ke Syria di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, putera dari Zaid bin
Harits ra yang gugur pada perang Mut’ah di tahun 8 Hijriah. Pengiriman
ekspedisi ini sempat diusulkan para sahabat untuk ditarik kembali ke Madinah
guna membantu mengatasi masalah dalam negeri seperti memerangi orang-orang
murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat dan memadamkan
pemberontakan-pemberontakan kecil.
Namun usulan ini ditolak dengan tegas oleh Abu bakar
karena pengiriman ekspedisi ini merupakan amanah dari Rasulullah saw. Sikap
tegas yang ditunjukkan oleh Abu Bakar kelak membuahkan hikmah tersendiri bagi
usaha penyelesaian konflik sosial di dalam negeri.
Selama 40 hari berperang melawan orang-orang Romawi di
Syria, akhirnya ekspedisi usamah meraih kemenangan. Keberhasilan ini
menimbulkan opini positif bahwa Islam tetap jaya, tidak akan hilang seiring
dengan wafatnya Rasulullah saw. Akhirnya satu persatu suku-suku yang semula
meninggalkan Islam kembali memeluk Islam dan loyal terhadap kekhalifahan Abu
Bakar al-Shiddiq.
Kini persoalan dalam negeri yang terakhir dan perlu
segera dipadamkan adalah pemberontakan yang digerakkan oleh nabi-nabi palsu
seperti Aswad ‘Ansi dari Yaman, Tsulaiha dari suku bani Asad di Arab Utara,
Sajah binti al Harits di Suwaid,dan Musailamah al-Kadzdzab, anggota suku Arab
Tengah.
Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid ra untuk manumpas
pemberontakan-pemberontakan tersebut dan berhasil memadamkannya. Demikian juga
terhadap gerakan kemurtadan dan suku-suku yang enggan membayar zakat dapat
diselesaikan dengan baik oleh Abu Bakar melalui perantaraan panglima perangnya,
Khalid bin Walid ra.
Setelah permasalahan besar dalam negeri dapat diatasi
dengan baik, abu Bakar memfokuskan pada kebijakan luar negeri yakni
menyelamatnya suku-suku Arab dari penganiayaan pemerintahan Persia. Untuk misi
ini, Abu bakar kembali mengirimkan Khalid bin Walid ra dengan pasukannya ke
Iraq dan akhirnya bertempur dengan tentara Persia di Hafir, pada tahun 12 H
(633 M).[17]
Pada 15 Dzulqa’idah 12 H, Khalid bin Walid ra, mengalahkan
musuhnya secara total dan menduduki seluruh Iraq Selatan. Ekspedisi berikutnya
adalah ke Syria membantu perjuangan Usamah bin Zaid untuk mengamankan daerah
perbatasan dari serangan orang-orang Romawi. Karena perbatasan merupakan
jalur-jalur perdagangan bangsa Arab.
Sekitar bulan Rabi’uts-Tsani 13 H yang bertepatan dengan
31 Juli 634 M. Akhirnya kekaisaran Romawi dapat ditumbangkan melalui perang
Ajnadin.[18]
Padahal dari sekian banyak pertempuran-pertempuran pasukan muslim jauh lebih
kecil dari pasukan lawan. Keberhasilan pasukan muslim mengalahkan pasukan lawan
tidak terlepas dari spiritual yang tinggi kaum muslimin seperti tersirat dalam
opsi yang disampaikan Khalid bin Walid ra maupun utusan-utusan muslim lainnya
kepada Kaisar Persia dan Panglima Perang Romawi.
Apa yang dilukiskan Khalid bin Walid ra tentang kondisi
mental spritual pasukan muslim memang tepat, karena mati syahid adalah dambaan
setiap muslim dengan ganjaran surga dan kekal didalamnya, apalagi kaum muslimin
saat itu yang berada dalam barisan pasukan muslim memiliki kualitas keimanan
yang tinggi dengan kesadaran akhirat yangtak tertandingi, sehingga kematian
bukanlah sesuatu yang menakutkan melainkan sesuatu yang didambakan karena yakin
akan adanya hari perhitungan atas segala amal yang diperbuat dan kehidupan
akhirat setelah kehidupan di dunia ini.
Di saat kemenangan demi kemenangan diraih pasukan muslim
di Ajnadin. Abu Bakar dikabarkan jatuh sakit tepatnya pada tanggal 7 Jumadil
Akhir, 13 H, dan akhirnya meninggal dunia setelah menderita sakit selama dua
minggu. Beliau meninggal dunia pada usia 61 tahun pada hari Selasa, 22 Jumadil
akhir, 13 H (23 Agustus 634 M).[19]
Meskipun Abu Bakar menjabat khalifah relatif singkat
yakni dua tahun tiga bulan, beliau berhasil membina dan mempertahankan ekstensi
persatuan dan kesatuan umat Islam yang berdomisili di berbagai suku dan bangsa.
Wibawa umat Islam pun semakin terangkat dengan ditaklukannya dua imperium
terbesar dunia saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kedua imperium ini menjadi
poros kebudayaan dan peradaban dunia. Karena penaklukan atau peletakan
kedaulatan umat Islam di kedua imperium itu menjadi aset yang sangat
berpengaruh bagi pembangunan peradaban dunia Islami. Hal itu terbukti dengan
peradaban Islam yang pernah jaya berabad-abad lamanya di Jaziarh Arab dan benua
Eropa.
Implikasi sejarah semacam ini tentu tidak teranalisis
pada masa kekhalifahan Abu Bakar, karena beliau berperang bukan dengan tujuan
kekuasaan melainkan semata-mata menegakkan syariat Islam dan menciptakan
kedamaian di mana pun umat Islam berada, pekerjaan besar semacam ini tentu
menguras energi tenaga dan pikiran yang sangat besar. Usia Abu Bakar yang
mencapai 60 tahun ketika dilantik menjadi khalifah, dan kerja keras yang
dilakukannya beresiko bagi kesehatan fisiknya, Abu Bakar pun jatuh sakit dan
meninggal dunia.
Prestasi lainnya adalah upaya pengumpulan Qur’an. Dari
dialog Umar bin khattab dengan Abu bakar bahwa begitu banyak para huffaz
Qur’an yang syahid di medan pertempuran sehingga dikhawatirkan oleh Umar dapat
merusak kelestarian Qur’an itu sendiri di masa yang akan datang.
Melalui kesaksian sejumlah sahabat yang pernah mendapat
pengajaran Al-Qur’an dari Rasulullah saw, dikumpulkan dan disalin kembali oleh
Zaid bin Tsabit ra atas instruksi khalifah Abu Bakar. Akhirnya Qur’an terhimpun
dalam bentuk mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf al-Imam (Mushaf Usman).[20]
Dari sekian prestasi yang terukir pada masa kekhalifahan
Abu Bakar, maka jasa terbesar Abu Bakar yang dapat dinikmati oleh peradaban
manusia sekarang adalah usaha pengumpulan Qur’an yang kelak melahirkan mushaf
Usmani dan selanjutnya menjadi acuan dasar dalam penyalinan ayat-ayat suci
Al-Qur’an hingga menjadi kitab Al-Qur’an yang menjadi pedoman utama kehidupan
umat Islam bahkan bagi seluruh umat yang ada di permukaan bumi ini.
.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, K. A Studi of
Islamic History, diterjemahkan oleh Gufran A, Mas’adi dengan judul Sejarah
Islam Mulai dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani: Tarikh Pra
Modern. Cet. II; Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan
Terjemahannya. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
Haekal, Muhammad Husain, As-Siddiq Abu
Bakr, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul Abu Bakar as-Siddiq
(Sebuah Biografi). Cet. II; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
Hisyam, Ibn. Al Sirah Al Nabawiah.
Jilid IV; Beirut. Dar Al Jil, 1987.
Al-Kandahlawy, Syaikh Muhammad Yusuf. Mukhtashar
Hayatush-Shahabat. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul Sirah
Shahabat. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
Khan, Majid Ali. The Pios
Caliphs, ditejemahkan oleh Joko S. Abd. Kahhar dengan judul Sisi hidup
para khalifah Saleh. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
Mu’nis, husain. ‘Alam al-Islam. Misra:
Dar al-Ma’arif, 1973.
Mubarakfuri, Syaikh Shafiyur Rahman. Ar-Rahiq
al-Makhtum Bahtrun fi as-Sirah an-Nabawiyah ‘ala Shahibiha afdhal as-Shalat
was-Salam, diterjemahkan oleh Rahmat dengan judul Sirah Nabawiyah.
Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 1998.
Nasution, Harun. Islam Rasional: Gagasan
dan Pemikiran. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996.
Nasution, Lahmuddin. Penerapan
Syariat Islam Pada Masa Khulafa` Ar-Rasyidin. Fosting Blog Internet pada
tanggal , 29 Jun 2006.
Sou’yb, Joesoef. Sejarah Daulat
Khulafaurrasyidin. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Syalabiy, Ahmad. Mausu’ah al-Tarikh
al-Islamiy wa al-hadarah al-Islamiyah, jilid I. Cet. VIII; al-Qahirah:
Maktabah al-Nahdah, 1978.
Al-Tabari, Abu Ja’far Ibn Jarir. Tarikh Al
Umam Wa Al Mulk. Jilid III; Kairo: Dar Al Fikr, 1979.
[1]Lihat Ahmad Syalaby, Mausu’ah al-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadarah
al-Islamiyah, Jilid I (Cet. VIII; al-Qahirah: Maktabah al-Nahdah, 1978), h.
380.
[2]Lihat Majid Ali Khan, The Pious Caliphs, diterjemahkan oleh Joko S.
Abd. Kahhar dengan judul Sisi Hidup para Kahlifah Saleh (Cet. I;
Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 17-18
[3]Lihat K. Ali, A Study of Islamic History, diterjemahkan oleh Gufran
A. Mas’adi dengan Judul sejarah Islam Mulai dari Awal Hingga Runtuhnya
Dinasti Usmani: Tarikh Pra Modern (Cet. I; Jakarta: Raja Grapindo Persada,
1997), h. 89.
[4]Lihat Ahmad Syalabiy, loc. Cit.
[5]Lihat K. Ali, Loc. cit
[6]Lihat Majid Ali khan, Op. Cit., h. 20.
[7]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV.
Toha Putra, 1989) h. 215.
[8]Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq al-Makhtum Bahtrun fi
as-Sirah an-Nabawiyah ‘ala Shahibiha afdhal as-Shalat was-Salam, diterjemahkan
oleh Rahmat dengan Judul Sirah Nabawiyah (Cet. 1; Jakarta: Rabbani Press,
1998), h. 718.
[9]Dalam definisi khalifah yang dikemukakan Majid Ali khan bahwa sejauh
menyangkut kekuasaan yang didelegasikan terhadap Hukum, dia adalah seorang
khalifah, seorang pengganti atau wakil dari Rasulullah SAW yang merupakan
“wakil Raja sesungguhnya”, Allah SWT di bumi, dan sejauh menyangkut eksekusi
(pelaksanaan) terhadap hukum, dia adalah Amir atau Imam, yakni pemimpin kaum
Muslim pada masanya.
[10]Ibn Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiah, (Jilid IV; Dar Al Jil, 1987), h.
225.
[11]Abu Ja’far Ibn Jarir Al-Tabari, Tarikh al Umam Wa Mulk, (Jilid, III;
Kairo: Dar AlFikr, 1979), h. 208.
[12]Ibn. Hisyam, op.cit., h. 228.
[13]Muhammad Husain Haekal, As-Siddiq Abu Bakr, diterjemahkan oleh Ali Audah
dengan Judul Abu Bakar as-Siddiq (Sebuah Biografi) (Cet. II; Bogor:
Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), h.48.
[15]Lahmuddin Nasution, Penerapan Syariat Islam Pada Masa Khulafa`
Ar-Rasyidin. Fosting Blog Internet pada tanggal , 29 Jun 2006.
[16]Syaikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawy, Mukhtashar Hayatush-Shahabat, diterjemahkan
oleh Kathur Suhardi dengan judul Sirah Shahabat (Cet. I; Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 153.
[17]Joesoef Sou’yb, Sejarah Daulat Khulafaurrasyidin, (Cet. 1: jakarta:
Bulan Bintang, 1979), h.24.
[20]Muhammad Husain Haekal, op.cit.,h. 341.
My Blog List